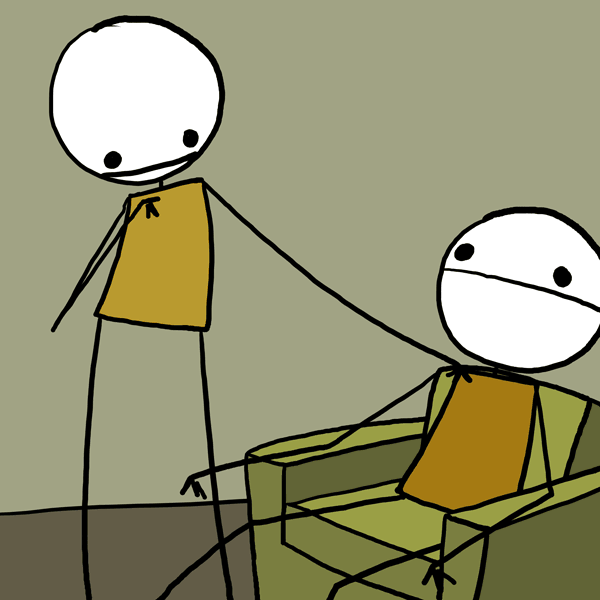| (Gola Gong) Manusia hanya bisa berencana,tapi Tuhan jualah yang menentukan." pepatah lama Jakarta malam di penghujung tahun bergolak. Segala jenis orang tumplek ke jalan. Terompet seharga dua ratus lima puluhan dan klakson jutaan bersahut-sahutan. Orang yang di kantongnya hanya cukup uang buat beli rokok, meramaikannya dengan duduk-duduk di pinggir jalan. Sedang yang kantongnya tebal lebih asyik menikmati suasana di bar dengan cognac atau dansa-dansi. Dan untuk golongan yang sederhana, cukup nonton acara TV saja, walaupun membosankan. Rumah sakit CBZ (sekarang RSCM). Remaja Roy duduk di sisi pembaringan. Menemani Toni yang berbaring meratapi nasibnya. Betapa putus asanya kawannya itu. Dia sengaja menemaninya malam itu. Orang tua Toni sendiri sedang menghadiri resepsi di instansi tempat bapaknya bekerja. "Andi bilang, kalau tabrakan biasanya yang mati yang dibonceng. Lantas dia menghentikan Enduronya. Menyuruhku memegang setir,” Toni memulai tentang tragedy itu. “Ayolah, aku capek, Ton, katanya. Sebenarnya aku juga capek. Tapi kelihatannya dia ngantuk sekali. “Aku jalankan motor pelan-pelan saja. Paling-paling lima puluh. “Kamu kayak banci saja, Ton! Andi mengejekku. Masa ngejalanin motor kayak gerobak sapi saja, ejeknya lagi. Aku diam saja. Tiba-tiba, Roy, ada ketakutan yang mencekam perasaanku. Mungkin firasat. “Lalu ada motor bebek menyusul. “Wah, sama bebek saja, kok kalah! Dia memanas-manasi. Aku susul saja motor bebek itu. Kebetulan juga ada motor GL dan RX sedang kejar-kejaran. Lengkap sudah emosiku tersulut. Apalagi si Andi nggak mau diam—memanas-manasiku terus. “Aku angkat roda depan, Roy! Aku kencangkan gas. Akumelesat! Aku salip mereka. Lantas Andi bersorak memberi semangat. Aku jadi lupa diri, Roy. Mulai dari Tangerang, kami selalu saling kejar. Dan aku selalu unggul di depan. “Lalu… Oh, Roy!” Toni memejamkan matanya. Dia seperti melihat tabrakan maut itu lagi. “Aku masih sempat meloncat, Roy. Aku nggak nyangka kalau ditikungan itu ada truk yang melaju kencang. “Aku sudah membunuh Andi, Roy,” Toni menangis. Meratapi nasib sobatnya. Kemudian dia memegangi kepalanya yang dibalut perban, dan paha kirinya yang diamputasi. Dia meringis kesakitan. Botol yang berisi cairan merah itu menetes satu-satu, mengaliri slang dan masuk ke urat nadinya. “Jangan terlalu dipikirkan, Toni. Siapa pernah tahu nasib seseorang?” Roy menenangkannya. “Oh, God! Kenapa ini musti terjadi? Aku cacat, Roy! Jalanku akan terseok-seok. Diperhatikan orang dan dicemoohkan! “Mengerikan! Aku rasa, lebih baik mati ketimbang begini.” Roy bisa menangkap kalimat yang mengalir tersendat-sendat dari sobatnya ini. Begitu putus asa. Seolah-olah hidup sebagai penyandang cacat itu adalah sesuatu yang hina. Padahal Tuhan berfirman, “Wahai umatku keturunan Adam dan Siti Hawa!” Bukan, “Wahai umatku yang normal atau umatku yang cacat.” Padahal Napoleon adalah seorang pria cebol untuk ukuran sana, si jelita Marlee Matlin seorang bisu tuli, dan Stevie Wonder pun seorang buta. Tapi Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terbaik buat umatnya. Percayalah ini! Sejarah sudah membuktikannya! “Kamu mau mendengar ceritaku, Ton?” Toni diam saja. Memejamkan matanya. “Oke, aku cerita saja. Terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Ini tidak lain, karena aku tidak ingin punya sobat yang cengeng dan banci macem kamu, “ Roy menyulut rokoknya dulu. “Di Bandung aku punya sobat. Hendra, namanya, Ganteng, pinter, jujur, dan kreatif. Kami satu sekolah. Kami sudah diibaratkan tidur seranjang, makan sepiring, dan minum segelas. Apa yang dia punya, juga punyaku. Begitu sebaliknya. “Ngeceng dan ngegombalin cewek adalah bumbu hidup kami. Juga dengan jeans pun rasanya hidup kami sudah komplet. Kami menmang bandel. Karena itu, kami juga bersaing sehat untuk menyeimbangkan antara kebandelan dengan prestasi. Kedengarannya enak kan, kalau ada yang ngomong, ‘biar bandel, tuh anak pinter juga’. Jangan deh macem begini, ‘udah bandel, goblok lagi!’ “Hidup kami memang selalu diisi dengan petualangan dan yang segala hal berbau sensasi. Tapi ada kelebihan kami masing-masing yang bertolak belakang. Aku dengan puisi dan cerita-ceritaku. Dia dengan kepiawaiannya menepuk bulu angsa. “Kami bersaing secara sehat. Biasanya, apabila puisi atau ceritaku dimuat, dia akan membalas kesombonganku dengan piala kejuaraan bulu tangkis. “Betapa bahagianya kami waktu itu. Punya banyak kawan. Semua orang menyukai kami.” Sampai di sini Roy berhenti. Menyulut rokoknya lagi—yang kesekian. Dia melihat Toni sedang memperhatikan seekor cecak di langit-langit bangsal. “Teruskan, Roy.” Ternyata dia mengikuti cerita itu. “Waktu itu kami sedang jalan di persimpangan Asia Afrika-Braga, ketika ada dua cewek centil di seberang jalan. Cewek Bandung kan sudah terkenal gareulis?” Roy tertawa kecil. “Biasa, kami gombalin. Hendra, kalau sudah masalah cewek, sukar dikendalikan. ‘Aku cinta keindahan!’ begitu katanya. Sedangkan yang indah-indah itu ada pada wanita cantik. ‘Ini bukan diskriminasi,’ alasannya. Hanya selektif saja,” Roy berhenti lagi. Menarik napas. Dia betul-betul ingin menghibur Toni agar bisa melupakan kegetirannya. Dan dia hanya bias melakukannya dengan bercerita apa saja. Pokoknya cerita saja. Ngomong apa saja. “Ya itu tadi. Siapa pernah tahu nasib seseorang?” kalimat terakhir ini begitu berat dan penuh teka-teki. Roy memandang ke luar lewat jendela. “Kenapa temanmu, Roy?” Nyatanya Toni sudah melupakan nasibnya sendiri—untuk sementara. Ini baik buat dia. “Aku nggak sempat mencegahnya ketika dia berlari menyeberang. Padahal waktu itu lampu menyala hijau buat pengendara kendaraan bermotor. Hendra memang ceroboh. “Aku hanya bisa berteriak menutup wajah!” “Kenapa, Roy?” “Ada sebuah mobil menerjangnya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Shock! masih terbayang ketika tubuh Hendra terseret beberapa meter oleh mobil jahanam itu. Aku pikir dia mati. “Kamu tahu apa yang dikatakannya ketika siuman dari pingsan selama satu malam?” Toni menggeleng cepat. Dia seperti menanti kelanjutan ceritanya. Roy memang paling ahli kalau sudah mendramatisir sebuah cerita, sehingga orang-orang yang mendengarnya akan larut terbawa arus cerita. “’Di mana ini? Di surga?’ katanya sambil menahan sakit. Aku bilang, ‘Di neraka! Nggak bakalan deh, surga mau nampung orang macem kamu!’ ledekku lagi. Dia hanya meringis ketika mendengar suaraku. “’Kamu licik, Roy!’ makinya padaku. ‘Kenapa nggak kasih tahu ada mobil waktu itu? Cewek sialan!’ makinya lagi kepada cewek-cewek yang kami gombalin waktu itu. “’Heh, mereka ada di sini,’ bisikku sambil menunjuk ke arah pintu. Cewek-cewek itu loyalitasnya tinggi juga. Padahal kenal aja belum. Baru maen mata di jalan doang. Tapi cewek-cewek itu memang sangat menyesal karena merasa terlibat dengan kecelakaan itu. “Lalu ketika dia menyadari ada sesuatu yang ganjil dengan kondisi tubuhnya, sedikit pun kami tidak mendengar suara tangis, penyesalan, atau keputusasaannya.” “Kenapa dia, Roy?” “Tangan kirinya diamputasi sampai ke sikut. Semua orang yang sedang menunggunya begitu tegang dan bingung harus berbicara apa kepadanya nanti. Tapi apa katanya ketika melihat tangan kirinya yang sudah buntung?” “’Cuman ini?’ katanya memegangi tangan kirinya. Sedikit pun tidak terlukis pada wajahnya rasa keputusasaan! Lalu apa komentarnya lagi? ‘Ah, ini aku anggap seperti kehilangan daging beberapa kilo saja. Malahan aku bersyukur, karena aku hanya bias berbuat dosa dengan satu tangan saja.’ “Kami hanya tertawa. Sense of humor-nya tidak hilang “Seharusnya kamu pun begitu, Ton! Apalah artinya tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya kalau jiwa kita sendiri cacat.” Rupanya inilah maksud Roy bercerita itu. Secara tidak langsung menyindir sobatnya agar tidak cengeng dan putus asa. “Yang paling penting ini, “ Roy menunjuk dadanya, “jiwa kita! Jasmani boleh cacat, tapi tidak jiwa kita. “Kita ini hanya titipan Tuhan. Semuanya akan dikembalikan pada-Nya.” Roy memperhatikan Toni yang menerawang entah ke mana. Dia berharap, semoga dengan cerita karangannya ini bisa menggugah semangat sobatnya, yang dulu begitu riang dan konyol. “Bulutangkisnya?” Toni memang sudah tertarik. Roy bersinar-sinar matanya, “Hendra nggak kehabisan akal. Setelah sembuh, dia berlatih serve dengan satu tangan. Katanya, hanya serve-nya saja yang mesti dilatih. Itu nggak gampang. Kalau nggak dibiasakan, akan mudah di-smash lawan. Tapi pada prinsipnya main bulutangkis itu kan yang dominant kaki. Bola kalau sudah di atas tinggal dipukul-pukul saja. “Nggak lama Hendra turun lagi ke gelanggang. Ikut event-event yunior. Memang nggak pernah juara. Dia hanya ingin menularkan semangat kepada pemain bulutangkis yang nggak cacat. “Jadi yang dibicarakan di sini adalah semangat, rasa optimis, dan motivasi. Juga belajar menghargai diri sendiri, apa yang kita punyai. Kalau kita sudah tidak bias menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita akan bisa hidup? Mau ke mana kita hidup? “Nggak kayak kamu, Ton, pengecut! Banci! Nggak berani menghadapi hidup hanya karena satu kaki!” “Kamu bilang aku banci, Roy?” suaranya mulai ada tekanan. Pada sorot matanya ada sebersit kilatan. Roy memang sengaja bermaksud menyulut emosinya. Semangat kelaki-lakiannya. Sudah hamper jam 00.00. Saat yang paling ditunggu-tunggu. Di sekitar Monas-Thamrin-Sudirman, sudah berderet mobil produk Jepang keluaran terakhir. Itu tidak membuat iri orang-orang yang membludak dengan modal dengkul. Yang penting sekarang adalah membunyikan terompet sekeras-kerasnya dan melupakan hal yang pahit di tahun kemarin. Lalu merangkai sesuatu yang manis di tahun yang baru. Di langit Jakarta malam ini kembang api banyak dilontarkan. Cahayanya pecah berbinar-binar. Aneka warni. Menghibur beribu pasang mata untuk melupakan sejenak ancaman resesi dunia. Sehingga bintang yang gemilang pun malam ini jadi malu untuk bersaing. “Teruskan cerita Hendra tadi, Roy.” “Menyadari dia nggak mampu lagi menyaingi pemain non cacat, akhirnya dia banting setir. Di Indonesia ini ada sebuah wadah yang menampung para olahragawan cacat yang berprestasi. YPOC, namanya. Yayasan Pembina Olah Raga Cacat. “Setiap empat tahun sekali, YPOC mengadakan pekan olahraga, seperti umumnya atlet non cacat dengan PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Dengan mengadakan pecan olahraga, diseleksi para atlet cacat yang kira-kira mampu menyumbangkan medali untuk dikirim ke event-event internasional. “Di sini memang belum dibicarakan soal prestasi. Tapi untuk saling memupuk rasa persaudaraan sesama orang cacat. Saling bertukar pengalaman dan berbagi rasa.” Roy menyulut rokoknya entah untuk yang keberapa. Toni meminta sebatang. Tapi Roy melarangnya. “Pernah suatu kali kami ngegombalin cewek lagi. Tapi ternyata cewek-cewek itu kampungan juga. Sudah hidup di zaman nuklir, kok masih ngebedain orang cacat dan non cacat. Aku marah sekali begitu mereka menghina Hendra. “Tapi apa reaksi Hendra? “’Kalian anak SMA?’ katanya kalem saja. ‘Diajari Undang-undang 45 dan GBHN, nggak? Coba deh cari, apa ada gitu pasal dan ayat berapa, yang melarang orang cacat ngegombalin cewek?’ begitu katanya. Malah sambil senyum. “Jadi yang aku pelajari dari sobatku itu adalah, dia selalu berusaha untuk masuk ke dalam dunia orang lain, orang non cacat umumnya. Dia ingin menghapus imej masyarakat tentang orang cacat yang disinyalir cepat tersinggung dan selalu ingin dibelaskasihani. “Contohnya, kalau kita melihat ada seseorang yang menyentuh nurani kita, akan terasa toh, betapa perasaan kita tersentuh, ingin menolong, dan ingin berbincang-bincang tentang kesedihannya. Tapi kita paling-paling memendamnya saja. Mau nanya, ‘Kenapa tuh, tangannya buntung? Kecelakaan ya?’ Atau, ‘Kamu buta sejak lahir?’ “Semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak pernah spontan terlontar. Semua orang memendamnya dalam hati. Mereka takut menyinggung perasaannya! “Itu nggak betul. “Hendra bilang, ‘Aku ingin tampil seutuhnya di depan masyarakat. Aku akan melayani keingintahuan mereka tentang perasaan orang cacat. Dan yang paling penting, aku ingin orang-orang pulang ke rumah dengan membawa kesan yang bagus tentang orang cacat.’ “’Ini memang impian,’ kata Hendra optimis. ‘Tapi akuakan mewujudkannya.’ “Nah, sekarang aku pingin nanya sama kamu.” “Tentang apa?” “Setelah sembuh, tentunya kamu harus berjalan menggunakan kruk. Dan ini cuma satu-satunya di sekolah kita bahwa, kamulah yang buntung kaki. “Ketika kamu tturun dari Combimu, memasuki sekolah, dengan diikuti berpuluh-puluh pasang mata, apa yang akan kamu lakukan dengan situasi itu? Bermacam-macam toh, karakter seseorang. Siapa tahu waktu itu ada yang mencemooh atau merasa iba sama kamu.” Toni terhenyak di pembaringan. Tangan kanannya meremas-remas seprai. Pertanyaan seperti itulah yang paling menakutkannya. Ya, apa yang akan aku lakukan ketika aku kembali masuk sekolah? Hatinya merintih. “Itulah yang aku pikirkan sekarang, Roy,” Toni menangis. “Dengan menangis, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluarnya, Ton.” “Lantas apa yang mesti aku lakukan?” “Bicaralah semaumu, seperti dulu kamu bicara, Ton! Berusahalah agar orang-orang tetap menganggap bahwa, Toni itu tidak berubah! Masih tetap konyol. “Carilah hal-hal yang bisa menetralisir suasana kaku. Biasanya yang lucu-lucu itu paling manjur untuk penyegar suasana. Ah, kamu kan ahlinya dalam melucu, Ton! “Kenapa sih mesti pusing hanya karena soal invalid? Sekarang kan ada kaki palsu. Kamu bisa pasang itu! Masih banyak, Ton, yang lebih menderita dibandingkan dengan kamu. Yang tidak punya kedua tangan, kedua kaki, seluruh anggota tubuhnya, yang lumpuh, dan ada malah yang hanya bisa berbaring saja di tempat tidur.” Mereka berpandangan. Tangan mereka saling bergenggaman. Roy kini baru bisa melihat lagi sorot mata jenaka dan cemerlang itu. “Besok kawan-kawan mau nengok ke sini. Sekarang mereka sedang ngerayain tahun baru di Monas.” Tiba-tiba wajah Toni berubah tegang. “Siapa-siapa?” “Cuman kawan-kawan sekelas.” “Plus Titin?” “Ya.” “Oh, God!” Toni menutup wajahnya. “Aku nggak mau nemuin mereka, Roy! Mau apa ke sini?” “Come on, Ton! Besok kan tahun baru. Apa salahnya kalau mereka dateng ke sini, ngucapin Happy New Year sama kamu?” “Ah! Tapi kenapa mesti Titin? Aku nggak mau ngelihat sorot mata yang sedih dan mengasihani aku nanti! Katakana sama mereka, Roy! Aku nggak ingin diganggu!” Roy menggeleng, “Kenapa kamu jadi cengeng begini, Ton? Cobalah belajar bersikap realistis, Ton!” “Apa yang harus aku katakan sama mereka?” “Say, Hello, misalnya. Atau, Happy New Year, friend! Nggak susah kan?! Yang penting, berusahalah agar mereka melihatmu tetap gembira seperti dulu.” Malam semakin larut. Terompet dan klakson sudah mulai menghilang. Tangan-tangan mereka juga sudah kelelahan berjabatan tangan. Tapi mungkin masih ada di salah satu sudut atau beberapa sudut belantara Jakarta, yang masih belum puas menghabiskan sisa malam tahun ini. Happy New Year! * * * Toni kelihatan necis dengan baju kotak-kotak krem. Wajahnya bersinar memantulkan rasa percaya diri. Rupanya dia ingin tampil maksimal di hari pertama tahun ini.“Bagaimana, Roy?” Toni membusungkan dadanya. “Look like a movie star!” Roy bahagia melihatnya. Sekitar jam tujuh, kedua orang tua Toni datang bersama kedua adik perempuannya. Heni, masih di SMP kelas dua, memasang seikat kembang di meja. Sedangkan Ina memberikan nasi bungkus kepada Roy. Gadis kecil yang baru kelas enam itu, tertawa lucu melihat Roy begitu lahap dan kelaparan dengan nasi bungkusnya. Tidak lama kemudian muncul suara gaduh, suara tawa remaja yang selalu energik dan optimis memandang hidup ini. Pakaian mereka memang kusut sehabis pesta semalam suntuk. Tapi wajah mereka bersinar cemerlang. “Happy New Year, friend!” seru Toni menyambut kawan-kawannya dengan gembira. Mereka saling pandang. Keheranan dan sangat gembira melihat Toni masih gembira seperti dulu. Mereka mengelilingi tempat tidur. Mereka bercerita apa saja. Saling melemparkan dan membagi-bagikan senyum bahagia hari itu. “Gimana, Ton, masih sakit kakinya?” suara Titin pelan. “Nggak ada masalah, Tin,” Toni tersenyum konyol. “Ini aku anggap seperti kehilangan beberapa kilo daging saja. “Bukan begitu, Roy!” Semua orang tersenyum dan tertawa. Betapa tabah dan gembiranya suara Toni. Yang paling bahagia melihat perkembangan baik ini, ya siapa lagi kalau bukan kedua orang tuanya. Anak kita sudah kembali, bisik mereka. Jiwanya. Semangatnya. Sedangkan remaja bandel itu hanya berdiri di sudut. Tubuhnya yang penat disandarkan di tembok. Sesekali dia menguap dan matanya terpejam. Ternyata cerita karangannya ada manfaatnya juga. Manjur juga buat obat. Sebenarnya kita tidak usah merasa minder menjalani hidup ini hanya karena kondisi tubuh kita cacat. Cobalah renungkan dan berusahalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kita. Janganlah kekurangan itu kita jadikan alasan untuk dibelaskasihani orang. Itu salah. Keliru. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk bersedih-sedih, atau meratapi nasib. Tapi berusaha dan berdoalah! Sinar matahari pagi yang sejak tadi terhalang awan, mulai membebaskan diri. Menerobos lewat dedaunan, dan masuk ke dalam ruangan. Kehangatan sudah menyelimuti seluruh ruangan. Orang-orang dan pasien-pasien saling berjabatan tangan. Betapa bahagianya Roy hari ini. (dari BALADA SI ROY : JOE, Gramedia Pustaka Utama, 1989) |
|